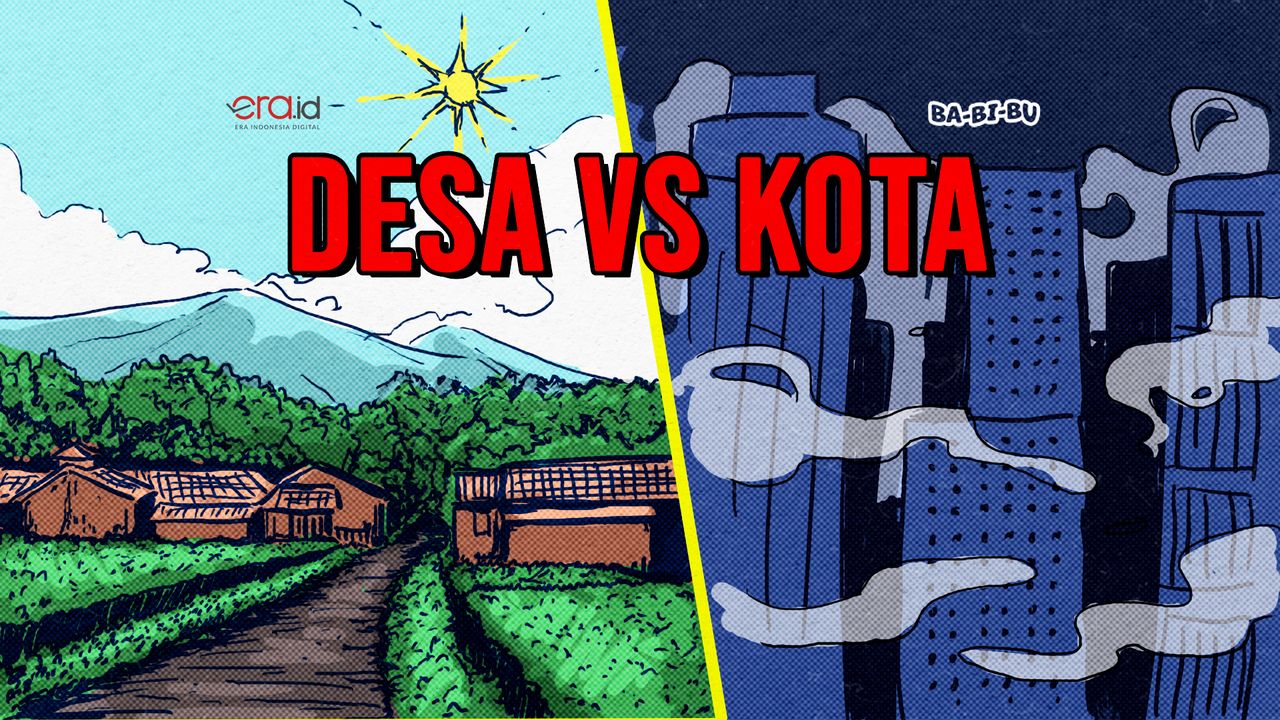ERA.id - Sejak dulu, selalu ada jarak antara desa dan kota yang diabadikan kata-kata. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa beserta segala padanannya (kampung, dusun, udik) acap diposisikan sebagai lawan dari kota. Sadar atau tidak, orang-orang juga menganggapnya demikian.
Saya ambil contoh dari nyanyian Gombloh. Ada lagunya yang terkenal berjudul Lestari Alamku. Di situ, ia menyandingkan alam dengan desa: Lestari alamku, lestari desaku. Desa dalam lagunya adalah tempat bocah-bocah bernyanyi di kala purnama dan bukit-bukit hijau berdiri.
Dalam lagunya yang lain, Gombloh menyanyikan tentang kota dengan judul optimis: Selamat Pagi Kota. Namun, penjabarannya amat terdengar kelabu. Kota dalam lagu Gombloh adalah tempat yang panas berbaur debu dan keringat di mana segala ketimpangan berada. Ada bocah gelandangan berdiri di depan toko roti hingga ibu dengan orok di pangkuannya menunggu warung kopi kaki lima.
Bagi Gombloh–dan mungkin banyak pendengarnya–desa adalah representasi kedamaian, sementara kota sebaliknya. Sama halnya anak zaman sekarang–seperti pekerja-pekerja kantoran di SCBD Jakarta–merujuk desa untuk menggambarkan healing atau jeda tetirah dari kepenatan kota.
Di sisi lain, orang-orang desa memandang kota sebagai penghidupan; tempat beradu nasib. Mungkin sama halnya dengan Eropa di mata imigran-imigran gelap dari Afrika yang kabur ke sana untuk memperbaiki hidup. Mereka tak pernah tahu apa yang menantinya di seberang lautan, tapi merasa hal itu patut dicoba.
Di antara sekian banyak pandangan soal desa dan kota dengan segala asumsi dan stereotipenya, saya pikir ada yang perlu dikoreksi. Misalnya bagaimana orang desa digambarkan dengan kepolosan dan keterbelakangan, sedangkan orang kota dianggap lebih berpikiran terbuka dan modern.
Mengguggat istilah kampungan dan udik
Saya tumbuh besar dengan tayangan-tayangan FTV di stasiun televisi swasta yang kisahnya mirip-mirip. Biasanya mereka menampilkan romansa antara dua sejoli dengan tingkat sosial atau ekonomi yang timpang. Si kaya dengan si miskin; bos dengan bawahan; atau orang kota dengan orang desa.
Orang desa yang saya tonton di FTV nyaris selalu ditampilkan dalam sosok gadis desa yang lugu, polos, dan tak tahu apa-apa. Deskripsi yang tak jauh berbeda dari opini kebanyakan orang–khususnya masyarakat perkotaan. Akhirnya, diksi seputar desa sering dikiaskan dengan negatif, seperti ungkapan “kampungan” atau “udik” yang seketika membuat kita membayangkan perilaku kurang beradab.
Kalau kita buka kamus, kata kampungan punya dua pengertian yang sama buruknya. Pertama, terbelakang (belum modern); kolot. Kedua, tidak tahu sopan santun; tidak terdidik; kurang ajar. Sementara salah satu pengertian udik menurut KBBI adalah: kurang tahu sopan santun; canggung (kaku) tingkah lakunya; kampungan.
Dalam prakteknya, orang-orang biasanya menyematkan kata kampungan bagi hal-hal yang nampak norak. Misalnya ketika orang-orang desa pertama kali ke ibu kota dan melihat langsung Monas dengan terkagum-kagum.
Saya juga pernah kedatangan keluarga dari desa yang baru pertama kali ke Jakarta. Saat saya jemput, sepanjang jalan ia menatap keluar jendela sambil bergumam dengan takjub, “Di atas langit masih ada langit, di atas flyover masih ada flyover.” Kalau saya cerita ini ke teman-teman kota saya, pastilah saudara saya itu dibilang kampungan.
Masalahnya, penyematan istilah tadi selalu memakai standar perkotaan sehingga menjadi bias. Kampungan dengan arti norak selalu dilihat dari kacamata orang kota menyaksikan orang desa ke kota. Padahal, bukan hanya orang desa yang norak. Siapa pun yang baru mencoba sesuatu untuk pertama kalinya dijamin norak.
Saya sampai hari ini masih heran dan takjub kalau kaca bisa melengkung dan layar hp bisa dilipat. Saya juga kegirangan waktu pertama kali menjajal kursi pijat elektronik di bandara. Dan saya berani taruhan banyak orang kota yang ngaku healing ke desa juga bersikap sama noraknya seperti bule-bule yang baru naik sepeda motor di Bali.
Saya pernah lihat ada selembaran promosi paket wisata ke desa. Isi kegiatannya: bertani dan menangkap ikan. Berarti ada orang kota yang rela merogoh kocek demi bisa menanam padi di sawah, mengarit, dan melempar jala. Bagi orang desa itu pekerjaan sehari-hari, tapi orang kota menyulapnya jadi komoditas.
Jika di balik, saya yakin tak ada orang desa yang mau membayar demi bisa merasakan sensasi mengetik di kantor. Dan bagi saya, pilihan ini lebih waras ketimbang orang kota yang buang-buang duit buat ikutan bertani dan naik kebo. Sekarang, siapa yang lebih norak?
Tak lebih polos dari orang kota
Saya baru menikah tahun 2022 kemarin. Keluarga yang berangkat dari Jakarta geleng-geleng kepala waktu menghadiri akad, karena rumah istri saya jauh di pelosok Bondowoso, dekat kaki gunung, jalannya sempit, dan mobil-mobil diparkir di sawah yang dikeringkan.
Semenjak menikah, sumber cerita saya soal kehidupan desa berasal dari mulut istri saya sendiri. Dan di kuping saya, itu tak terdengar selalu polos, lugu, dan menenangkan seperti bayangan orang-orang kota yang doyan healing ke desa. Sama seperti kehidupan di kota tak melulu buruk, begitu juga kehidupan di desa tak melulu baik.
Orang kota sering kita dengar berwatak materialis, apa pun dihitung dengan uang. Di desa ternyata tak jauh berbeda. Di kampung halaman istri saya, misalnya, ada tradisi pamugih. Jadi, setelah menikah, pihak perempuan bakal menyediakan rumah untuk ditinggali pengantin baru. Sementara perabotan rumah tangga: kasur, kursi, meja, lemari, dan barang-barang lain, bakal ditanggung pihak lelaki. Seserahan barang-barang pengisi rumah dari suami ke istri ini namanya pamugih.
Tradisinya sendiri tak jadi soal, sama-sama menguntungkan kedua pihak. Namun, masalahnya, tiap penyerahan pamugih bakal jadi omongan antar tetangga antar warga. Bukan hal yang asing jika pengantin baru ditanya-tanya berapa harga perabotan rumahnya. Kalau mahal bakal jadi omongan, setidaknya ada tetangga baru yang bisa diutangi. Kalau terlampau murah juga jadi bahan omongan, dianggap sebagai menantu yang kurang menjanjikan.
Di antara dua pilihan ini, banyak orang lebih memilih dipandang kaya daripada serba kekurangan. Makanya, kata istri saya, pamugih jadi ajang adu gengsi. Makin banyak pikap yang mengantar barang, makin terpandang. Makin tinggi kualitas kayu furniturnya, makin dianggap terpuji. Demi gengsi itu, beberapa rela meminjam uang berlebih ke sanak famili biar bisa beli perabotan mahal.
Bukan hanya pamugih, mas kawin juga jadi bahan omongan, termasuk pesta kawinan. Di dusun istri saya, ada mantan kepala desa yang besanan dengan Pak Lurah yang punya anak perempuan. Acara akad diadakan di tempat Pak Lurah, sedangkan resepsinya di rumah mantan kepala desa.
Melihat hajatan di tempat Pak Lurah besar-besaran, konon sepulangnya dari sana besannya sesumbar ke tetangga-tetangga bakal mengadakan acara yang lebih besar lagi, mengalahkan Pak Lurah. Berita itu menyambar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Pak Lurah. Walhasil, waktu resepsi, pihak keluarga perempuan tak ada yang datang selain mempelainya. Saya hanya geleng-geleng kepala dengar cerita tadi, ampun deh!
Itu hanya sekelumit gambaran betapa orang desa tidak sepolos dan selugu yang dipikirkan orang kota. Ada kalanya, walau tidak selalu, hidup di desa harus siap mendengar celotehan tetangga seperti halnya mendengar rekan kerja yang suka menjilat atasan. Begitulah hidup. Tak ada yang sempurna selama kita masih hidup, tidak di kota, tidak juga di desa.