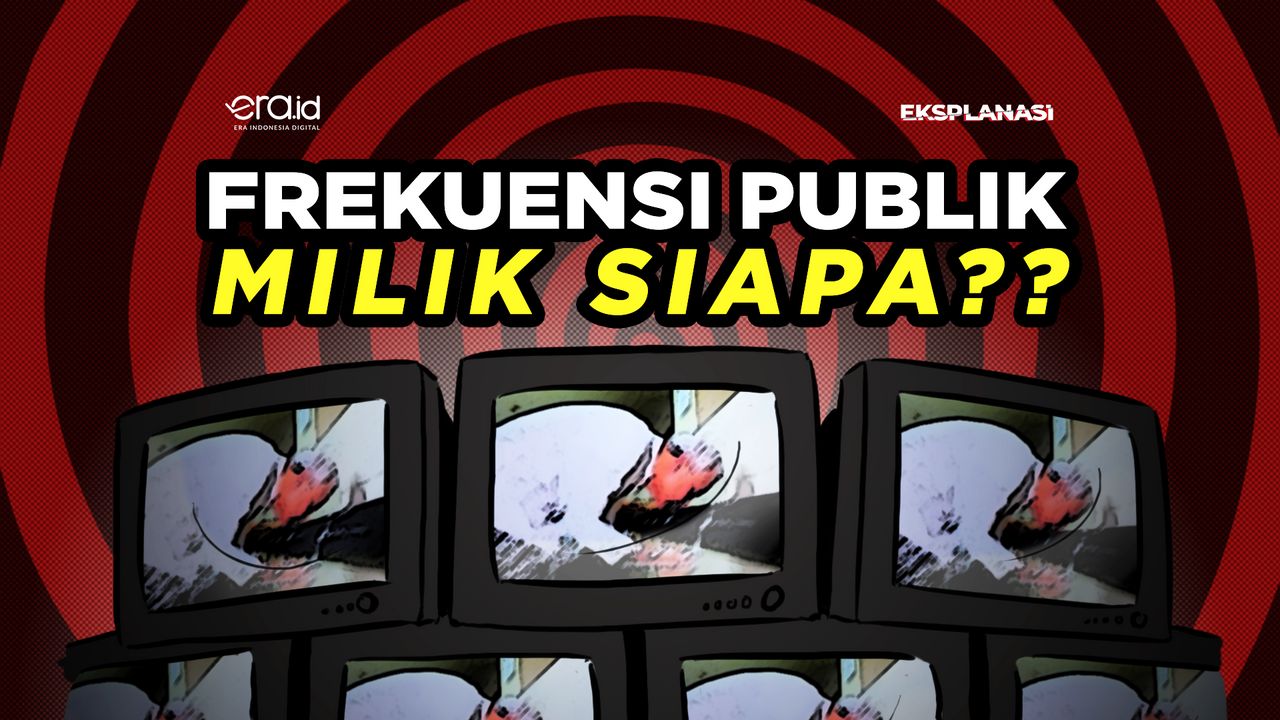ERA.id - Pada awal 2000-an, publik sempat gempar dengan penampakan yang diduga hantu menyerupai kuntilanak dalam tayangan azan Magrib di Trans TV. Tahun ini, publik kembali dihebohkan oleh tayangan azan Magrib dengan penampakan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di dalamnya.
Durasi azan Magrib tadi kurang lebih tiga menit dan Ganjar berkali-kali disorot kamera, mulai dari masuk ke masjid; mengambil wudhu; hingga salat berjemaah. Banyak pihak mengkritiknya, termasuk bekas anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ade Armando yang kini berstatus sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Aturan KPI sendiri mengatakan bahwa di dalam siaran azan tidak boleh ada iklan, apalagi iklan politik,” kata Ade di Jakarta Barat, Senin (11/9/2023). “Orang bisa saja mengatakan bahwa tampilnya Ganjar di sana bukan lah iklan, tapi itu kan mengada-ada ya, itu pasti iklan namanya.”
Video azan Magrib yang memicu polemik itu ditayangkan stasiun RCTI sejak Selasa (5/9/2023). Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga sempat memberikan pernyataan keras di media sosial.
Ia menulis surat terbuka yang isinya peringatan kepada konglomerat media merangkap pemilik partai politik (parpol) dan tim sukses agar menghentikan penggunaan frekuensi publik untuk kepentingan partai dan bacapres yang mereka usung.
“Hormati demokrasi!” tandas Fahri di platform X, Sabtu (9/9/2023).
RCTI sendiri merupakan media di bawah naungan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Bhakti Investama, di mana Hary Tanoesoedibjo menjadi direktur utamanya. Ia tak lain juga merupakan Ketua Umum Partai Perindo yang masuk dalam koalisi pendukung Ganjar.
Ada banyak lagi konglomerat media yang merangkap sebagai elite politik, antara lain: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang terkenal memiliki banyak media, salah satunya Metro TV; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mengakuisisi Jak TV dari Jawa Pos Group; hingga Aburizal Bakrie yang punya PT Visi Media Asia di bawah Grup Bakrie.
Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) sebelum pemilihan umum (Pemilu) 2014 lalu mengeluarkan laporan soal demokratisasi media. Menurut laporan itu, industri media yang cenderung dikuasai oleh segelintir orang dan terkonsentrasi di Jakarta rentan bias.
Kepemilikan perseorangan itu bahkan bisa menelikung prinsip-prinsip demokratis dan mengancam kualitas ruang publik penyiaran, seperti kualitas tayangan yang seragam dan pelanggaran penggunaan frekuensi publik untuk kepentingan politik.
"Regulasi sektor lain pun tidak mengantisipasi ini. Ambil saja Undang-Undang Pemilu yang tidak mengantisipasi adanya pola-pola penggunaan media oleh pemiliknya sebagai pamflet politik; aturan iklan kampanye politik yang terlalu teknis prosedural sehingga mudah diakali kontestan; serta perlakuan yang sama antara iklan politik dengan iklan produk yang lain," tulis laporan berjudul Kepemilikan dan Intervensi Siaran tersebut.
Curi start kampanye pada masa sosialisasi
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 28 Tahun 2018, peserta pemilu disebutkan dapat melakukan kampanye melalui iklan kampanye di media cetak, media daring, media sosial, dan penyiaran. Bentuknya bisa berupa tulisan; suara; gambar; atau gabungan antara semuanya.
Namun, dalam Pasal 37 Ayat (5), ada tambahan berbunyi: Peserta Pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita.
Perlu dicatat bahwa aturan di atas berlaku selama masa kampanye berlangsung. Untuk Pemilu 2024, itu berlangsung mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Sebelum tiba masanya, parpol peserta pemilu hanya bisa melakukan sosialisasi internal dan dilarang mempertontonkannya ke publik.
Lebih lanjut, dalam Pasal 25 Ayat (25) disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempublikasikan citra diri atau karakteristik parpol melalui media cetak, elektronik, maupun daring, yang memuat tanda gambar dan nomor urut parpol.
Adapun penampakan Ganjar dalam tayangan azan Magrib di RCTI, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, bukanlah kampanye karena Ganjar belum menjadi peserta pemilu.
“Capres tidak? Bakal capres tidak? Kan belum daftar," ujar Rahmat di Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Namun, ia tetap mengimbau para bacapres untuk menahan diri dalam menggunakan frekuensi publik dalam tahapan sosialisasi.
“Kami minta yang akan menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden agar menahan diri untuk tidak melakukan sosialisasi melalui frekuensi publik, salah satunya melalui media elektronik," katanya di ruang Media Center Bawaslu, Jakarta, Selasa (12/9/2023), dikutip dari situs Bawaslu.
Frekuensi publik memang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan golongan tertentu. Demikian menurut anggota KPI Pusat, Aliyah, dalam "Diskusi Media dan Aturan Pemberitaan Kampanye Pemilu", Rabu (9/8/2023), di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat.
“Kita tidak bisa menutup mata akan hal tersebut, masih banyak TV yang menyiarkan partainya sendiri, bahkan cenderung tidak berimbang,” jelas Aliyah.
Hubungan kepemilikan media penyiaran dengan pemilik parpol, menurutnya, memungkinkan mereka menyiarkan blocking segment berupa acara parpol berdurasi panjang.
Kepemilikan media penyiaran yang terhubung dengan pemilik parpol memungkinkan untuk menyiarakan blocking segment. Sering dijumpai siaran langsung yang memberitakan acara sebuah partai dengan durasi yang panjang.
Fenomena mencuri start kampanye pada masa sosialisasi juga acap menghiasi frekuensi publik. Seperti halnya iklan jingle Partai Amanat Nasional (PAN) yang kerap muncul beberapa waktu terakhir dan menampilkan nomor urutnya pada Pemilu 2024 nanti.
Ketika frekuensi milik publik direbut elite politik
Ketua PR2MEDIA Amir Effendi Siregar mengatakan, ada dua prinsip dalam demokratisasi media yang harus ditegakkan: Kebebasan dan keberagaman. Pertama, jaminan adanya kebebasan berekspresi, berbicara, dan kemerdekaan pers. Kedua, keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), keberagaman isi (diversity of content), dan keberagaman pendapat (diversity of voices).
"Tanpa keanekaragaman (diversity), akan terjadi pemusatan, konsentrasi, dan monopoli oleh yang kuat terhadap lemah atas nama kebebasan dan kemerdekaan," tulisnya dalam laporan Kepemilikan dan Intervensi Siaran (2014).
Demi menegakkan asas keberagaman kepemilikan, UU Penyiaran menerapkan aturan pembatasan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran.
Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), penguasaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang terpusat pada suatu badan hukum atau perorangan harus dihindari karena dapat menimbulkan "monopoli informasi" dan berpotensi menciptakan "pengendalian opini publik oleh pihak tertentu".
Namun, dalam prakteknya, kedua hal yang dikhawatirkan tadi sudah berlangsung sejak lama akibat hubungan kepemilikan media dengan elit-elit politik tertentu. Dalam studi kasus tahun 2013 misalnya, PR2MEDIA menemukan masih banyak pemberitaan media yang tidak independen.
“Dari 56 berita politik yang menjadi sampel, sebanyak 19 berita (33,9%) di antaranya menampilkan pemilik media dan afiliasi politiknya,” tulis laporan tersebut. “Ironisnya, dari 19 berita yang melibatkan pemilik sebagai objek pemberitaan tersebut, semuanya atau 100% berita berorientasi positif.”
Penelitian tadi menyimpulkan, peta kepemilikan industri media–khususnya televisi–masih dipegang segelintir orang. Ditambah lagi, para pemiliknya menggunakan media mereka untuk kepentingan ekonomi dan politik masing-masing.
“Kepentingan ekonomi digunakan ketika media diorientasikan untuk ‘menggebuk’ lawan bisnisnya atau demi melindungi perusahaan bisnisnya sendiri dari liputan negatif,” bunyi kesimpulan tadi.
Adapun kepentingan politik bermuara pada dua tujuan utama: pencalonan diri dalam pemilu atau aktivitas pemilik sebagai ketua parpol tertentu.
“Industri memerlukan garansi politik, dan, karena itu, mereka berusaha dekat dengan kekuasaan. Inilah yang membuat liputan-liputan sering kali bias,” tulis laporan tersebut. “Ambisi dan kepentingan-kepentingan pemilik dalam konteks politik pada akhirnya menciptakan produk berita yang bias, tidak objektif.”