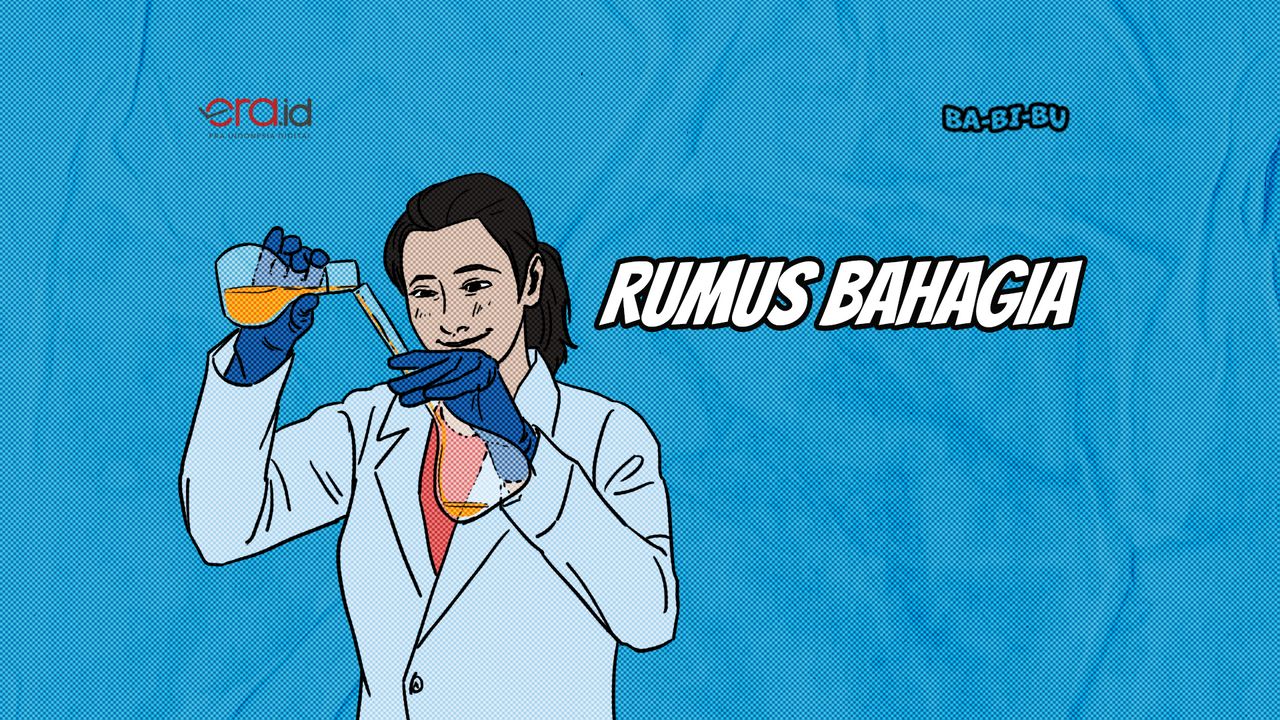ERA.id - Tahun pertama kuliah, seorang senior pernah menasehati saya begini, "Standar kebahagiaan kita terlalu tinggi, berbanding terbalik dengan standar kesedihan kita yang terlalu rendah." Saya bertanya, 'apa contohnya?' Ia lalu memaparkan beberapa kejadian yang sering kita alami.
Ketika sedang asyik menikmati secangkir kopi, entah tersenggol atau tidak sengaja ketendang sampai tumpah, hampir selalu kita mengumpat dalam hati, kesal, dongkol, dan pada kasus yang menimpa saya, itu akan ditambah mencak-mencak serta mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh.
"Bahkan kehilangan segelas kopi saja sudah kita tangisi!" lanjutnya sambil mengepulkan asap ke depan muka. Mengenaskan sekali, parameter kesedihan kita tak lebih tinggi dari segelas kopi. Itu belum ditambah dengan gelas yang pecah, kepeleset saat lewat lantai yang licin, ketumpahan kecap, atau pakaian bolong terkena sundut rokok.
Standar kesedihan yang terlalu rendah ini menciptakan generasi cengeng sosial. Orang-orang yang menganggap bahwa mereka seolah-olah memikul seluruh penderitaan manusia di muka bumi. Generasi yang tidak segan menulis curahan hati mereka pada pamflet yang akan dibaca khalayak umum!
Lalu sialnya lagi, ini semua ditambah dengan miskin bahagia, alias kekurangan dosis untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena yang kita cari lebih sering terlalu tinggi, muluk-muluk, bahkan buat hal yang sederhana sekali pun.
Pendeta William Ockham mencetuskan gagasan yang kemudian dikenal dengan hukum Occam's Razor, dalam bahasa Latin berbunyi: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. 'Janganlah mengandalkan banyak hal daripada yang benar-benar perlu.' Begitu terjemahan yang ditulis dalam novel Mark Haddon, Insiden Anjing di Tengah Malam yang Bikin Penasaran.
Jadi begini, kita bisa menemukan solusi dari suatu masalah terkadang justru lewat hal-hal yang sederhana, dengan membuang sisanya yang rumit-rumit. Karena seringkali jawaban yang kita cari mungkin sudah di genggaman tangan, tetapi kita malah sibuk mencari di kolong-kolong meja, bawah kasur, dan mengorek-orek dapur.
Dalam mencari kebahagiaan, kita sering terjebak dalam negeri utopia yang rumit. Kebahagiaan dibatasi kepada kepemilikan materi, benda-benda yang mampu memuaskan hasrat, atau kekuasaan yang begitu tingginya untuk menengok ke bawah.
Hal-hal ini, walaupun tidak selalu, hampir pasti menjadi indikator kebahagiaan manusia. Ini manusiawi, tetapi terkadang sering membentur rambu-rambu kemanusiaan. Kita bisa jadi gelap mata. Dan kebahagiaan yang hanya memuaskan hasrat semata akhirnya menjadi candu.
Candu ini kembali ke apa yang dibilang senior saya dulu, bahwa standar kebahagiaan kita terlalu tinggi. Cara menurunkan dosisnya tentu dengan merendahkan standar kebahagiaan terhadap diri sendiri.
Jadi, ketika kopi yang belum sempat kita seruput tumpah, kita bahagia karena gelasnya tidak ikut pecah. Jika gelasnya pecah, kita masih bisa bahagia karena pecahannya tak menggores kulit. Jika pecahannya sampai melukai, kita tetap bahagia karena lukanya masih bisa ditutup dan tidak kekurangan darah terlalu banyak sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Begitu seterusnya.
Rangkaian "jika dan jika" ini selalu bisa menjadi sebab kita menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang normalnya kita ratapi. Untuk mengimbanginya, tentu perlu untuk ikut meninggikan standar kesedihan masing-masing. Sehingga kita bisa terus melangkah tidak peduli berapa pun kopi yang tumpah. Jika kita percaya hakikat segala sesuatu akan kembali ke sisi-Nya, seharusnya kita bisa merelakan kehilangan-kehilangan yang sempat kita pinjam wujudnya.
Bahagia di atas penderitaan orang
Dalam sebuah studi kasus, rumusan tentang kebahagiaan diterbitkan. Setelah diselenggarakan uji coba, disimpulkan bahwa, "Ketidakseimbangan akan mengurangi kebahagiaan rata-rata, baik ketika orang mendapatkan lebih banyak atau ketika mereka mendapatkan kurang dari orang-orang yang ada di sekitar mereka," kata Robb Rutledge, peneliti dari University College London.
Kesimpulan tadi mengingatkan saya dengan kisah Gua Penyesalan. Begini ceritanya, syahdan seorang raja mengutus tiga orang untuk mencari mata air keabadian. Ketiga utusan tadi lalu menempuh perjalanan panjang dan berliku, mereka bertanya ke setiap orang yang ditemui untuk mengorek informasi soal mata air itu. Hingga tibalah mereka di depan sebuah gua yang teramat gelap.
Menurut desas-desus, itu adalah gua penyesalan. Konon gua itu dipenuhi bebatuan dan pasir di sepanjang jalan, dan mereka yang memungut atau tidak memungutnya akan sama-sama menyesal. Ditambah lagi gua itu hanya bisa dimasuki sekali.
Masuklah ketiga utusan tadi ke dalam gua. Seorang utusan mengumpulkan banyak-banyak batu yang ia rasakan di kakinya ke dalam kantong. Seorang lagi hanya mengambil sedikit. Sementara yang terakhir enggan memungut apa pun sepanjang gua. Mereka bertiga berjalan sambil meraba-raba dinding gua untuk menuju pintu keluar.
Sesampainya di luar, betapa kagetnya mereka saat membuka isi kantong kedua utusan. Ternyata bebatuan dan pasir dalam gua tadi berupa emas dan perak. Sontak saja ketiganya menyesal. Yang pertama menyesal karena tidak mengambil lebih banyak lagi, yang kedua menyesal karena mengambil terlalu sedikit, yang terakhir paling menyesal karena tidak mengambil apa pun.
Namun, dua orang pertama yang kebagian emas dan perak bisa sedikit lega dan bahagia karena mengetahui ada kawan mereka yang tak kebagian sedikit pun. "Masih untung dapat segini," batin mereka. "Daripada tidak dapat sama sekali."
Menurut hitungan matematis, banyak variabel yang dibutuhkan untuk menentukan kebahagiaan, termasuk imbalan, harapan, dan apa yang terjadi kepada orang lain. Namun, tentu saja kita harus sepakat bahwa kebahagiaan yang didapatkan dari ketidakbahagiaan orang lain, atau istilahnya "berbahagia di atas penderitaan orang", merupakan bentuk kezaliman. Dan jenis kebahagiaan seperti itu harusnya kita hindari.