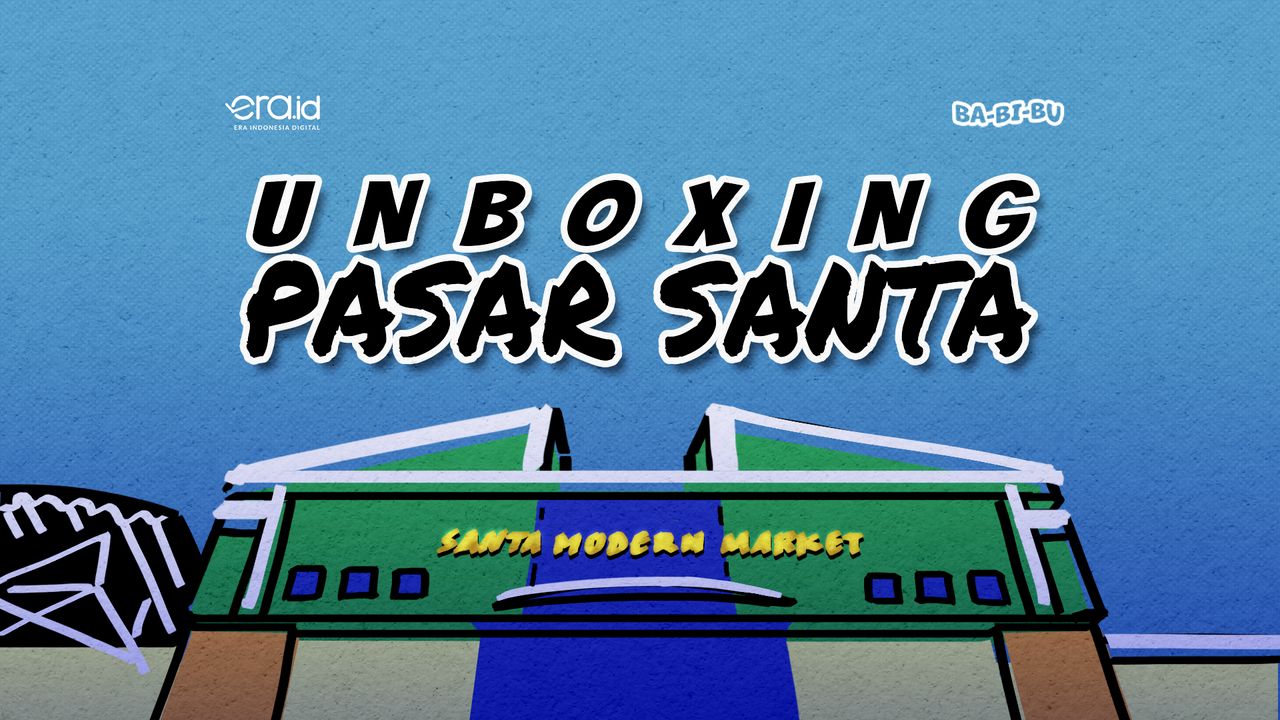ERA.id - Hari ini muda-mudi Jakarta mungkin lebih mengenal M Bloc sebagai titik kumpul yang asik, atau lebih lawas lagi, Blok M Plaza di dekatnya yang sudah terhubung dengan Stasiun MRT. Namun, tak jauh dari kawasan itu, dulu ada pasar yang ramai disinggahi dan menawarkan banyak cerita, tak lain adalah Pasar Santa. Kini, meski tak seramai dulu, pasar itu masih menarik dikunjungi dan punya magnetnya sendiri—setidaknya bagi saya.
Rabu (22/11/2023) lalu, saya mengelilingi Pasar Santa hampir setengah hari. Bagi yang memilih transportasi umum, kami sarankan naik MRT dan turun di Stasiun Blok M, lalu melanjutkan perjalanan dengan ojek online. Bagi pengendara pribadi, untungnya tak ada juru parkir liar dalam pasar. Jadi siapkan saja uang elektronik untuk bayar parkir.
Saya disambut dengan tulisan besar-besar di pintu masuk utama: SANTA MODERN MARKET. Hari sudah siang saat saya sampai dan pasar tampak sibuk: Orang lalu-lalang; mesin-mesin jahit berisik; dan bau kopi menguar dari lantai paling bawah—lantai yang tampaknya paling sesak.

Meski tampak tinggi menjulang dari luar, di dalamnya Pasar Santa hanya terdiri dari tiga lantai: Basemen, lantai dasar, dan lantai 1. Basemen berisi kedai-kedai kopi dan roastery. Dari sanalah aroma biji-biji kopi dipanggang dan serbuk-serbuk kopi diseduh berasal.
Lantai dasar dipenuhi toko-toko kelontong, pernak-pernik, salon, dan lapak-lapak tukang jahit. Beberapa warung kopi dengan menu kaki lima juga dibuka di sana. Banyak kipas angin bergeleng di depan kios-kios pedagang. Dan saya melihat penjaga toilet tertidur di mejanya. Seorang penjaga toko baju berbisik, “Kalau mau kencing sekarang aja, itu yang jaga kalo ada orang teriak juga gak bakal bangun.”
Ini catatan penting untuk pengunjung Pasar Santa, pastikan sedia uang receh kalau mau ke toilet. Sekali buang air kecil Rp2.000; buang air besar Rp4.000.
Beberapa kios sudah tampak tutup di lantai dasar, tetapi masih banyak yang buka. Di antaranya sudah melapak selama bertahun-tahun, misalnya toko baju Here to Stay milik vokalis band Straight Answer, Aca. Saya menyempatkan mampir ke sana dan membeli kaos mereka yang sedang promo.
Here to Stay sendiri diambil dari judul lagu band metal asal Amerika, Korn yang rilis tahun 2002. Dan toko Here to Stay milik Aca menjual baju-baju band khususnya genre hardcore. Tempatnya kecil saja, dalamnya hanya cukup dimasuki sekitar 6-7 orang. Kaos-kaos band dipajang di luar, ada yang digantung, ada yang terhampar di meja.

Paling sering saya temui tentu kaos-kaos dari Straight Answer. Beberapa lagi yang saya kenali seperti The Jansen dan kaos “Timur” dari The Adams ikut menggantung di beranda. Sayang gajian masih seminggu lagi. Saya hanya bisa menatap nanar. Lalu Aca menunjuk deretan baju di meja, “Yang itu lagi promo, stoknya mau habis.”
Pergelangan tangan Aca dibalut perban. Ia cerita habis jatuh saat dibonceng temannya. Kebetulan yang membonceng juga penjaga toko Here to Stay, Nurdin namanya. Saya melihat Nurdin berjalan di depan toko dengan setengah pincang.
Keduanya pindah ke Pasar Santa sejak 8 tahun lalu. Mereka sempat menikmati kejayaan pasar itu sebelum jatuh ditiban pandemi. “Waktu pandemi, habis. Untung masih buka toko online,” kata Nurdin. Di masa-masa lockdown ia juga tetap nekat menunggui tokonya karena butuh makan. Hanya saja waktu itu ia hanya buka sampai jam 5 sore.

Pandemi berlalu, pasar dibuka lagi, tapi banyak pengunjung telah melupakan eksistensinya. Meski begitu, Aca dan Nurdin masih memilih bertahan. Bagi Aca, Here to Stay dan Pasar Santa bukan hanya toko, tapi tempat berkumpul dan bertemu teman-temannya—termasuk para penggemar.
“Apalagi pas puasaan, waduh banyak banget yang mampir,” cerita Aca. “Jauh-jauh, ada yang dari Depok, Cibinong, bela-belain ke sini mau ketemu.” Waktu kemarin saya ke sana, kebetulan juga ada penikmat Straight Answer dari Palembang sedang mampir.
Setelah membungkus kaos putih Straight Answer, saya pamit ke Aca dan Nurdin. Mereka menyarankan saya untuk mampir ke toko baju bekas Fight Back dan bertemu Fendi, sang owner. “Kalau mau cari baju-baju vintage, di situ, konsultasi aja ke dia, sepuh itu di perkaosan,” pesan Nurdin.
Saya tak berlama-lama di lantai dasar karena bukan itu yang menjadi daya tarik Pasar Santa sesungguhnya. Kita harus naik setingkat lagi untuk merasakan sisa-sisa kejayaan pasar itu medio 2014 silam. Di lantai paling atas, lantai 1, jiwa Pasar Santa bersemayam, termasuk toko Fight Back yang disebut-sebut tadi.
Berburu kaus vintage di Santa
Naik ke lantai 1, suasana baru terasa agak sepi. Pertama-tama kita akan disambut deretan food court dengan range harga di bawah Rp50 ribu. Nasi kuning, mi, siomay, dimsum, burger, gorengan, dan beberapa menu lain cukup lengkap untuk pilihan makan siang pekerja kantoran di sekitar Pasar Santa.
Kata beberapa pedagang yang saya temui, Pasar Santa paling ramai memang waktu jam makan siang atau akhir pekan. Di luar itu, para penjaga toko lebih sering menganggur.
Kontras dengan dua lantai sebelumnya, kios-kios di lantai 1 lebih banyak yang tutup. Dan bagi yang baru pertama kali ke sana, agaknya harus menyiapkan diri. Entah hanya perasaan saya atau bukan, tetapi denah lantai 1 seperti labirin. Mungkin karena banyak kios tutup, saya jadi sering berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama seperti disesatkan jin gunung—padahal bukan pertama kali itu saya ke Pasar Santa.
Tujuan pertama saya adalah Fight Back. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya saya bertemu dengan Fendi. Rambutnya memanjang melebihi bahu; dahinya tampak lebar; janggutnya dipotong rapi; dan ia mengenakan kaos hitam yang umurnya lebih dari 15 tahun. Meski perawakannya tampak seram, sekalinya tersenyum dan mengobrol ia langsung terasa ramah.

Sudah tujuh tahun Fendi membuka tokonya di Pasar Santa. Sementara hobinya mengumpulkan kaus vintage sudah dimulai sejak tahun ‘90-an. Rata-rata kaus miliknya berusia di atas 15 tahun. Dan ia sama sekali tak menyangka pandemi justru melambungkan harga koleksinya di rumah.
Harga kaus vintage Fendi yang dibawa ke Fight Back saja dibanderol seharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan, salah satu kaus langka di rumahnya pernah ditawar seharga Rp30 juta. “Gak gua lepas, soalnya value-nya bisa lebih tinggi lagi,” kata Fendi sambil tertawa.
Saya memintanya menunjukkan kaus termahal di Fight Back. Ia lalu merogoh kotak di bawah meja dan mengambil dua lembar kaus bergambar potret Morrissey muda yang baru saja gagal konser di Indonesia. Masing-masing seharga Rp3,5 juta dan Rp4 juta. Kali ini, meski sudah gajian sekali pun, saya takkan kepikiran untuk membeli salah satu kaus itu.

Toko Fight Back memang didedikasikan untuk para kolektor. Namun, pengunjung Pasar Santa tak perlu khawatir. Bagi yang berminat belanja kaus murah, masih banyak toko thrifting di lantai 1 yang bisa dihampiri. Mereka biasanya juga menjual pernak-pernik lucu seperti aksesoris dan action figure.
Usai memanjakan mata dengan kaus-kaus vintage, saya melangkahkan kaki menuju Cigar Man, satu-satunya toko cerutu di Pasar Santa.
Menikmati cerutu lokal Indonesia
Gran Cigaro, Dos Hermanos Maduro, Malecon, Boslucks, Sultan Robusto. Saya membaca nama-nama asing berjejer di lemari kaca Cigar Man milik Pak Rama. Lelaki tua—taksiran saya sudah kepala 5—bersuara lirih dan berat itu mengenakan kaus The Smashing Pumpkins. Ia mempersilakan saya masuk ke tokonya yang sederhana.
Dua pelanggan sedang duduk menikmati cerutu masing-masing, mereka tampak ahli. Saya perokok, tapi sejujurnya belum pernah menghisap cerutu dengan benar. Dan Pak Rama dengan ramah menunjukkan koleksi cerutu miliknya. “Semua produk lokal,” ucapnya.
Darinya juga saya tahu kalau daun tembakau buat cerutu lokal paling banyak diproduksi di Jember, Jawa Timur. Bahkan, ada tembakau asli Kuba dibudidayakan di sana. Saya diajarkan tiga jenis tembakau dalam sebatang cerutu, ada dekblad (pembalut), omblad (pembungkus), dan filler (pengisi).
“Filler ini seperti saus dalam kretek,” kata Pak Rama. Saya mengangguk-angguk tak sabar ingin mencicipi.

Pak Rama menjual cerutu termurah seharga Rp25 ribu sebatang. Sementara paling mahal di kisaran Rp700 ribu. Saya bilang saya pemula, tolong kasih saya coba cerutu yang murah tapi masih lumayan enak di lidah. Lalu Pak Rama menyodorkan sebatang cerutu bermerek Tobaksgud. “Ini Rp50 ribu.” Dan ia memangkas sedikit ujung cerutu dengan alat pemotongnya.
“Jangan ditarik ke dada, dihisap di mulut saja, kumur-kumur, lalu keluarkan,” kata Pak Rama menuntun. Saya menurut. Jujur, lidah saya kurang cakap menilai rasa. Bagi saya itu hanya terasa pahit seperti kopi.
Saya tak menghabiskan cerutu itu di tempat. Pak Rama memotongnya lagi, menyimpannya di plastik, dan menyuruh saya membawanya pulang. Andai saya penikmat cerutu, mungkin saya bisa lebih menghargai rasa yang sempat singgah di mulut itu. Namun, walau pemula sekali pun, pengalaman yang diberikan Pak Rama tetap terasa mewah dan hangat.
Menutup hari dengan iringan vinyl di Laidback dan belanja buku di Post Santa
Sehabis menyesap cerutu pertama saya, perjalanan berlanjut ke toko piringan hitam tertua di Pasar Santa: Laidback Blues Record. Toko itu berdiri sejak 2014 dan segera menjadi magnet yang menarik lebih banyak pengunjung ke sana.
Bino, sang penjaga toko, sedang membersihkan piringan hitam di luar dengan iringan lagu blues. “Masuk aja, nanti nyusul,” ucapnya sambil meneruskan pekerjaannya.
Laidback sudah tampak asik sejak melihat jendela luarnya, dan makin terasa asik begitu melewati pintu masuk. Ruangannya terasa sempit dan memanjang. Sepanjang pandangan, ratusan piringan hitam tersusun rapi di rak-rak—sebagian digantung dan ditempel ke tembok. Stiker-stiker memenuhi jendela dan kasir. Beberapa poster album lawas dan film juga menghiasi celah yang tersisa.

Mata saya segera teralihkan dari poster biru bertuliskan “Sudahkah Anda Sembahyang?” kepada poster film dewasa tepat di sebelahnya. Pemeran pria berdiri di belakang pemeran perempuan berbaju setengah kedodoran memperlihatkan sebelah dadanya.
“Itu oleh-oleh Bos habis dari Jepang,” Bino menjelaskan. “Dulu kita punya juga vinyl backsound bokep, sekarang udah enggak ada.” Saya manggut-manggut. Katanya, vinyl model begitu biasa dipakai DJ untuk efek musik.
Saya melihat ada dua alat pemutar vinyl dalam toko. Sebelah kiri tersambung dengan speaker di luar, sementara satunya digunakan dalam ruangan. Saya request diputarkan lagu yang cocok menemani suasana sore hari di Pasar Santa. Bino meraih sebuah piringan hitam dari rak atas. “Ini yang sekarang lagi banyak didengerin.”
Ia memutarkan album rekaman Miki Matsubara. Suara simbal membuka lagu pertama, ck ck ck. Ah, nada yang tak asing ini pasti “Stay With Me”.
To you, yes my love to you…
Kata orang kualitas rekaman piringan hitam lebih baik ketimbang kaset dan digital. Entah apa saya tersugesti, tapi suara Miki sore itu terdengar lebih renyah daripada yang biasa saya dengarkan di Youtube.

Sayangnya, saya hanya bisa sempat mendengar satu lagu karena jam keburu hampir Magrib. Sebelum pulang, saya menyempatkan mampir ke salah satu toko buku di sana: Post Santa. Shinta, salah seorang penjaganya, sedang asik menghirup uap vape di luar toko buku bercat kuning itu.
Rambutnya kini lebih pendek dari yang saya lihat terakhir kali. Namun, senyumnya masih seperti biasa, sama dengan jadwal buka Post Santa yang tak pernah berubah. Libur Selasa dan Kamis. Buka dari jam dua siang hingga jam tujuh malam.
Berbeda dengan toko buku lain, Post Santa tidak menjual buku-buku dari penerbit besar. Koleksinya tentu jadi lebih sedikit. Namun, kita bisa menemukan banyak judul yang tak dijual di toko-toko buku besar seperti Gramedia.
Sore itu, saya membeli kumpulan puisi karya teman saya, Nunu, berjudul “Apakah Membenci Hidup Sama dengan Mencintai Kematian?”. Sebelum pamit, saya menyempatkan diri bertanya ke Shinta. “Dari dulu aku penasaran, toko buku kecil begini apa nutup buat sewa bulanannya?”
Ia tersenyum dengan senyum yang tak pernah berubah seperti jadwal buka Post Santa. “Nutup.”